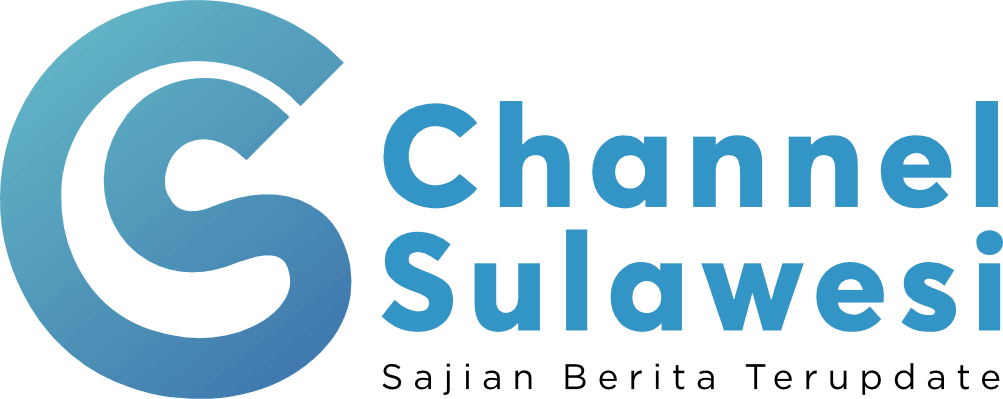Dalam genggaman dua perempuan itu, gemal-gemal padi terikat rapat. Toba mereka, pakaian adat suku Kulawi, melilit erat tubuh, memberi pernyataan diam tentang identitas yang mereka jaga dengan bangga.
Asap kemenyan mengepul dari tempurung di depan mereka, mengabur tipis ke udara, membawa harum yang menyelip ke hidung, seakan menyatukan manusia dengan alam dan leluhur.
Di tengah lingkaran itu, Said Tolao duduk bersila. Bibirnya terus bergerak, menggumamkan gane-gane, syair doa-doa dalam bahasa Kulawi dialek mouma.
Hawa sunyi menyelimuti, seperti udara yang tenang sebelum hujan deras mengguyur bumi. Orang-orang mulai menunduk, mengikuti bait demi bait doa yang mengalun. Seperti padi yang merunduk dalam syukur, mereka hanyut dalam ritme mantra yang menghidupkan kembali semangat tanah ini.
Di sekeliling Said Tolao, lingkaran manusia membesar. Beragam pakaian adat menghiasi tubuh mereka, dari toba hingga halili kain kulit kayu, ikat kepala siga hingga talienu. Desa Toro, atau Ngata Toro dalam bahasa lokal, menyambut mereka setelah perjalanan panjang dari berbagai pelosok.
Hari itu, Kamis 29 Agustus 2024, menjadi hari yang tak akan terlupa. Sebuah rumah adat Lobo kembali berdiri, lebih dari sekadar bangunan kayu, ia adalah simbol kebangkitan dan harapan, setelah bencana gempa tahun 2018 merubuhkannya.
Pompede Lobo, prosesi peresmian rumah adat itu, menjadi semakin bermakna dengan kehadiran rego wunca, sebuah ritual yang sudah lama dinantikan. Dalam tarian yang sarat makna itu, Said Tolao memimpin gerakan, mengajak semua yang hadir untuk merasakan ritme bumi dan langit.
Tujuh syair utama mengalun, dalam dialek mouma yang mengandung pesona kuno, pesona yang seakan memanggil roh-roh penjaga hutan dan gunung, memanggil kita untuk mendengarkan.
Salah satu syair itu bergema:
“Wua masumala tumai mantako
Ratodengkalae maku bula
Liwo tesenamo ncario dala
Buranga ntua rapotalilika
Sawa langi mombewe ripuna
Mokaso walo mo’ata dopi
Mparawaturea mengkomogugi”
Syair itu bukan sekadar kata-kata, melainkan sebuah ajakan, sebuah seruan untuk menjaga alam dengan cinta yang tulus, bukan merusaknya.
Bagi Said Tolao dan banyak lainnya, setiap bait rego wunca adalah pesan leluhur yang disampaikan melalui angin, air, dan tanah.
Rukmini, Tina Ngata atau kepala kampung perempuan Desa Toro, berbicara dengan ketegasan lembut.
“Sudah 15 tahun kami tidak melakukan wunca. Bencana gagal panen ini mungkin adalah teguran. Dulu, leluhur kita tahu caranya mengambil dari alam, dan tahu bagaimana berterima kasih,” katanya, seakan suaranya menyatu dengan desir angin yang membawa harum tanah.
Langit siang itu begitu biru, menyimpan pesan yang tak terucap. Saat anak-anak berebut makanan yang disematkan di pohon bambu, prosesi adat pun pecah menjadi sorak gembira.
Di Ngata Toro, dalam kesederhanaan yang penuh makna, rego wunca kembali mengalun setelah 15 tahun senyap. Ini bukan sekadar tarian, ini adalah harmoni yang ditemukan kembali, antara manusia dan alam yang harus terus terjaga, hari ini dan seterusnya.
Penulis : Mugni Mayah MAL