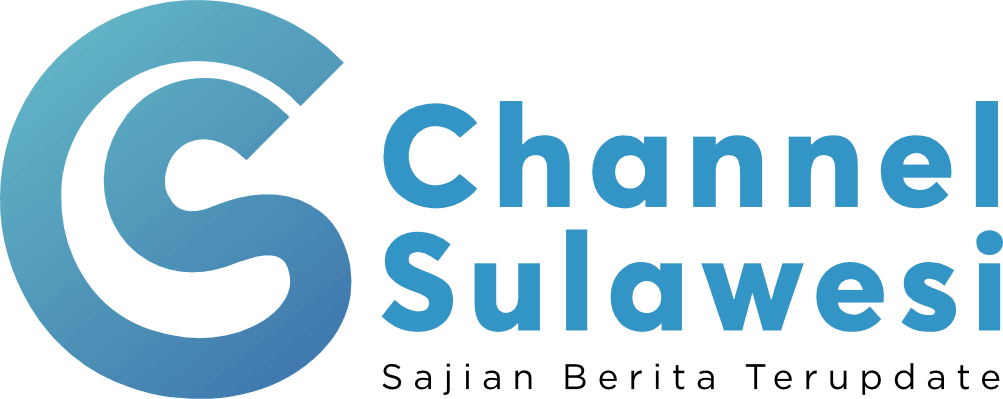Di balik deru kemajuan zaman dan kompleksitas dunia pendidikan, ada satu sosok yang kerap luput dari sorotan. Sosok yang hadir sejak hari pertama seorang anak mengenal huruf, mengeja kata, hingga perlahan menemukan makna hidupnya.
Dialah guru. Bukan guru besar, bukan profesor, bukan tokoh pendidikan nasional, melainkan guru biasa yang mengajar di ruang kelas yang bocor, menyapu papan tulis dengan tangan sendiri, pulang sore naik sepeda, dan tetap tersenyum meski gaji tak seberapa.
Guru biasa bukan berarti perannya kecil. Justru di tangan mereka, benih-benih masa depan bangsa ditanam. Di hadapan murid-murid yang beragam latar belakangnya, guru biasa menjalankan tugas suci: mendidik dengan hati.
Bukan sekadar mentransfer pengetahuan, melainkan membentuk karakter, menanamkan nilai, dan menjadi teladan dalam laku. Mereka ingin kita terhindar dari pahitnya kebodohan dalam kehidupan dunia yang keras ini.
Namun, terlalu sering kita menjadikan guru sekadar bagian dari sistem, bukan jiwa dari pendidikan itu sendiri. Mereka diminta menjalankan kurikulum yang terus berubah, diwajibkan mengikuti pelatihan, mengisi data digital yang melelahkan, tetapi tak pernah sungguh-sungguh didengarkan suaranya.
Ironisnya, dalam banyak kebijakan pendidikan, guru kerap hanya diposisikan sebagai pelaksana, bukan pemikir. Padahal, siapa yang lebih memahami denyut kebutuhan anak didik kalau bukan mereka?
Satu hal yang sering kita lupa: guru bukan hanya profesi, tetapi panggilan jiwa. Ia bukan sekadar bekerja dari pukul tujuh pagi hingga dua siang, tetapi menghadirkan diri sepenuhnya bagi anak-anak yang sedang tumbuh dan mencari jati diri. Banyak guru yang diam-diam membawa pulang tugas murid, memeriksa lembar demi lembar di malam hari, sementara anaknya sendiri belum sempat ia temani belajar. Banyak pula yang tetap hadir di kelas meski sedang tidak enak badan, karena merasa absen sehari pun bisa membuat anak-anaknya kehilangan arah.
Sikap-sikap seperti itu tidak bisa dibeli dengan pelatihan atau tunjangan. Ia lahir dari cinta. Dari keyakinan bahwa menjadi guru adalah ibadah panjang, yang pahalanya tak selalu diukur dengan materi. Bahkan mungkin, tak akan pernah sepenuhnya diterima di dunia.
Namun kenyataan di lapangan kerap tak berpihak pada mereka. Guru-guru honorer di pelosok negeri masih harus berjuang dengan penghasilan yang jauh dari kata layak. Ada yang mengajar pagi dan bekerja serabutan sore harinya demi mencukupi kebutuhan hidup.
Ada pula yang puluhan tahun mengabdi, tapi tak kunjung diangkat menjadi pegawai tetap. Mereka adalah penjaga api pendidikan yang tetap menyala di tempat-tempat yang tak tersentuh sorotan media.
Di sisi lain, masyarakat pun sering tanpa sadar bersikap tidak adil. Guru yang sabar mendidik anak-anak kita kadang justru disalahkan saat anak tidak naik kelas. Padahal, mendidik bukanlah proses sepihak.
Ia adalah kerja sama. Guru mendidik di sekolah, orang tua melanjutkan di rumah. Jika kita ingin anak-anak tumbuh dengan nilai dan budi pekerti, maka tanggung jawab itu tak bisa sepenuhnya dibebankan ke pundak guru seorang diri.
Ada baiknya kita mulai menata ulang cara pandang terhadap guru tak hanya sebagai pengajar, melainkan sebagai penjaga peradaban. Mereka tidak hanya mengisi kepala anak-anak dengan informasi, tetapi membentuk hati dan wataknya. Guru bukan sekadar bagian dari sistem pendidikan, tetapi penentu arah masa depan bangsa.
Tugas kita adalah menjaga martabat mereka. Bukan hanya dengan memberi fasilitas, tetapi dengan memperlakukan mereka sebagai manusia merdeka: bebas bersuara, bebas mengembangkan metode, bebas berinovasi sesuai kebutuhan murid. Jangan batasi mereka dengan tumpukan administrasi atau target kelulusan yang kaku.
Biarkan mereka mendidik dengan cara yang paling mereka pahami, karena tak ada satu pun sistem yang dapat menggantikan sentuhan pribadi seorang guru.
Sebab pada akhirnya, bangsa ini akan menjadi seperti apa tergantung pada siapa yang mendidiknya. Dan selama masih ada guru-guru biasa yang setia menjaga lentera pengetahuan, kita patut yakin bahwa masa depan belum kehilangan arah.
Dalam tradisi pesantren, sosok guru atau kiai memiliki kedudukan yang mulia. Santri bukan hanya belajar dari apa yang diajarkan, tetapi juga dari bagaimana sang kiai menjalani hidup. Ilmu dan akhlak berjalan seiring. Maka, di tengah hiruk-pikuk pendidikan modern yang sering kehilangan arah, barangkali sudah saatnya kita kembali menengok model relasi guru dan murid ala pesantren: relasi yang dilandasi kepercayaan, keteladanan, dan cinta ilmu.
Guru biasa yang mengajar di madrasah pelosok, di sekolah swasta kecil, atau bahkan di ruang kelas darurat pascabencana, sesungguhnya sedang menjalankan tugas luar biasa. Mereka menyalakan lilin di tengah gelap, menghidupkan harapan pada anak-anak yang nyaris putus asa. Mungkin tak ada nama mereka dalam buku sejarah. Namun dari ruang kelas sederhana itulah lahir pemimpin-pemimpin masa depan.
Maka, jika hari ini kita bicara tentang perbaikan pendidikan, mari mulai dari mereka. Dengarkan cerita guru-guru biasa. Beri ruang bagi suara mereka dalam menyusun kebijakan. Hargai mereka bukan sekadar dengan upah yang layak, tapi dengan pengakuan atas martabatnya sebagai pendidik.
Sebab pada akhirnya, kemajuan bangsa ini tidak hanya ditentukan oleh teknologi atau kebijakan hebat, tetapi oleh guru-guru biasa, yang dengan cinta dan kesabarannya, membentuk kita menjadi manusia-manusia luar biasa.
Penulis : Auliana Aqillah (mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)