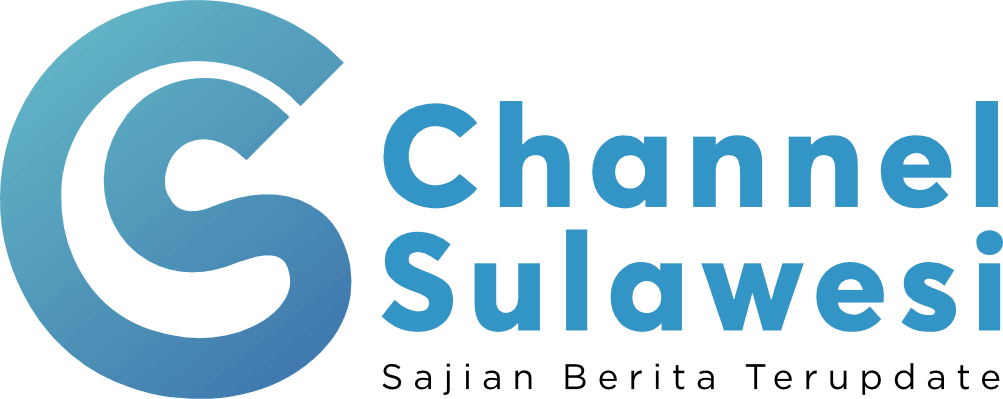Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), yang terbentang indah di pesisir utara Sulawesi Tengah (Sulteng), bukan hanya anugerah bentang alam. Ia adalah rumah bagi ribuan petani dan nelayan yang hidup dari kesetiaan mereka pada tanah dan laut.
Dari sawah, ladang, kebun, hingga Teluk Tomini yang kaya, Parimo adalah salah satu lumbung pangan daerah bahkan nasional.
Namun di balik pesona itu, mengintai bahaya yang tak kasat mata, kapitalisme birokrat. Ia adalah wajah baru dari penjajahan ekonomi, ketika kuasa politik menjelma menjadi alat akumulasi kekayaan oleh segelintir elit. Sebuah ancaman serius bagi masa depan kedaulatan pangan.
Kapitalisme birokrat terjadi ketika birokrasi tak lagi berfungsi sebagai pelayan rakyat, tetapi menjadi pedagang dengan privilese. Mereka mengatur regulasi, menguasai distribusi, memonopoli perizinan, dan diam-diam menjalin kongsi bisnis dengan pengusaha.
Lahan pertanian berubah fungsi demi proyek-proyek yang menguntungkan segelintir elite. Distribusi pupuk, solar, dan bibit yang mestinya untuk petani, justru disaring oleh tangan-tangan politik.
Izin tambang dan perkebunan dikeluarkan tanpa memperhitungkan dampaknya terhadap ketahanan pangan lokal.
Semuanya dibungkus rapi dengan nama “pembangunan”. Tapi di balik retorika itu, petani ditinggalkan. Gabah dihargai rendah, pupuk langka, dan pasar dikuasai tengkulak yang berjejaring dengan elite kuasa.
Petani Parimo bukan malas, bukan tidak inovatif. Mereka bekerja keras, bahkan turun-temurun menggarap tanah dengan nilai-nilai kearifan lokal.
Tapi ketika sistem tak berpihak, ketika keputusan diambil tanpa mendengar suara mereka, maka yang tumbuh bukan kesejahteraan, tapi keputusasaan.
Alih-alih menjadi subjek pembangunan, mereka diperlakukan sebagai objek yang diatur dan dikorbankan. Proyek pembangunan besar tidak jarang justru menyingkirkan mereka dari ruang hidupnya sendiri.
Parimo tidak kekurangan potensi. Ia bisa menjadi wilayah mandiri pangan, bahkan model kedaulatan pangan nasional.
Tapi itu hanya mungkin jika keberpihakan politik berubah. Bukan lagi mengutamakan pertumbuhan yang semu, tetapi pemerataan yang adil.
Perubahan itu tidak datang dari atas. Ia harus dibangun dari bawah, dari kesadaran politik rakyat sendiri. Petani, nelayan, pemuda, perempuan, dan jurnalis harus bersatu dalam gerakan yang menuntut transparansi, menolak monopoli kekuasaan, dan memperjuangkan tata kelola yang adil serta demokratis.
Pertarungan di Parimo hari ini bukan sekadar soal harga gabah atau akses pupuk. Ini adalah soal siapa yang menguasai sumber daya, dan untuk siapa ia dimanfaatkan. Jika sumber daya dikuasai birokrasi yang haus kapital, maka rakyat akan terus menjadi korban dari kebijakan yang menjauh dari akarnya.
Tapi jika rakyat bersatu, mengorganisasi diri, dan memperjuangkan kedaulatan atas tanah, laut, dan kebijakan, maka Parimo bisa menjadi contoh bahwa kedaulatan pangan bukan impian, melainkan kenyataan yang bisa digenggam.
Oleh: Mawan,S.Sos (Wartawan Media Alkhairaat)