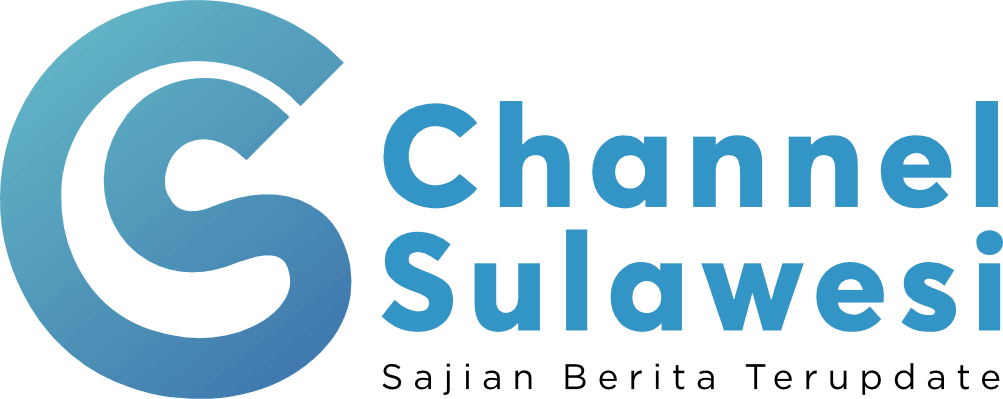Di sebuah rumah sederhana di Kecamatan Pinembani, Kabupaten Donggala, malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Waktu menunjukkan pukul 23.30 WITA.
Dalam pelukan sang istri, Agnes Hartuti Tarima, seorang pria terbaring lemah. Ia menarik napas berat, lalu… diam.
“Jatuh pas di sini,” ucap Agnes sambil menunjuk dadanya.
“Saya dengar betul, dia mendengkur sekali… lalu diam,” kisahnya.
Itulah akhir dari perjalanan hidup Ariel Sharon, seorang penyuluh Keluarga Berencana (KB) yang selama hampir satu dekade mengabdi di wilayah terpencil Sulawesi Tengah (Sulteng).
Ia tak berpulang di rumah sakit berfasilitas lengkap, bukan pula di tengah keluarga besar. Ia mengembuskan napas terakhir di tengah medan pengabdian yang jauh dari gemerlap kota, namun begitu dekat dengan denyut kebutuhan masyarakat.
Ariel adalah satu dari sedikit penyuluh KB yang bersedia ditugaskan di wilayah terisolasi. Medan menuju lokasi tugasnya bukan hanya sulit, tapi juga menantang nyali. Jalur berlumpur, tanjakan terjal, dan jalan rusak adalah teman hariannya.
Sejak 2016, Ariel setia menjalankan tugasnya di Desa Bambakaenu dan Dangara’a, dua titik yang bahkan tak semua peta digital bisa mengenalnya. Ia bukan hanya membawa data, formulir, atau modul penyuluhan. Ia datang membawa harapan, bahwa pelayanan negara juga menyentuh akar rumput paling dalam.
“Kadang saya tanya, ‘kenapa kamu senyum terus? Tapi memang begitu orangnya,” kata Agnes lirih.
“Penduduknya banyak, dusunnya berjauhan, tapi dia selalu semangat,” tutur Agnes.
Ariel meninggal dalam pelukan istri, tapi pulangnya bukan di atas mobil ambulans atau kendaraan dinas. Tidak ada fasilitas medis yang bisa menjemput jenazahnya. Mobil Puskesmas rusak. Jalanan rusak. Maka keluarga membawanya dengan sepeda motor. Motor yang baru saja ia beli pada April lalu.
Jenazah dibaringkan di atas rangka kayu, dibungkus kain jarik, dan dibonceng sejauh 75 kilometer menuju Palu.
Perjalanan itu bukan sekadar pengantaran jenazah, melainkan gambaran sunyi dari pengabdian tanpa pamrih. Di setiap tikungan jalan berlumpur yang dilintasi motor itu, seolah tergurat kisah betapa negara ini masih memerlukan banyak Ariel-Ariel lainnya.
Namun dibalik itu, ada jeritan lembut kehilangan atas kepergian Ariel.
“Papa… papa…”
Itulah suara kecil yang terus memanggil di malam setelah pemakaman. Putra Ariel, Azarel Kenley Huma, tak mengerti bahwa ayahnya tak akan lagi pulang dari tugas.
Biasanya, setelah bekerja, Ariel akan bermain dengannya. Namun kini, yang pulang hanyalah kenangan dan senyum terakhir yang tak akan pernah kembali.
Ariel Sharon tidak pernah tampil di layar televisi nasional. Namanya jarang disebut dalam laporan kinerja atau pidato pejabat tinggi. Tapi jejaknya ada di tiap rumah yang ia datangi, di tiap data keluarga yang ia catat, dan di setiap jalan sunyi yang ia tempuh dengan keyakinan bahwa negara harus hadir, meski melalui langkah seorang diri.
Kini, nama Ariel Sharon bukan lagi sekadar nama di daftar ASN. Ia telah menjelma menjadi simbol dari ketulusan pengabdian.
Ia tidak berpulang di tengah riuh, tetapi di tengah masyarakat yang ia cintai. Ia telah menempuh jalan panjang, demi sampai ke pelukan terakhir orang-orang yang mencintainya.
Dan di tengah hening hutan Pinembani, mungkin angin akan terus membawa namanya, Ariel Sharon, penyuluh KB, cahaya kecil dari pedalaman Sulteng yang tak akan pernah padam.
Kepergian Ariel menggugah banyak hati. Menteri Kemendukbangga/BKKBN, Wihaji menelepon langsung sang istri, menyampaikan bela sungkawa dan rasa hormat.
“Saya yakin tugasnya luar biasa dan penuh dedikasi. Tuhan memberikan jalan terbaik bagi suami Ibu yang telah bekerja luar biasa di lapangan,” ujar Menteri melalui video call.
Tak lama, Pemerintah Kabupaten Donggala pun berjanji memperbaiki akses jalan ke Pinembani dan menambah armada layanan kesehatan.
Dari tanah yang jauh dari pusat kekuasaan, suara duka Ariel ternyata menggema hingga ke pusat-pusat kebijakan. Mungkin inilah caranya sebuah kematian berbicara lebih nyaring dari kehidupan yang diam-diam. *