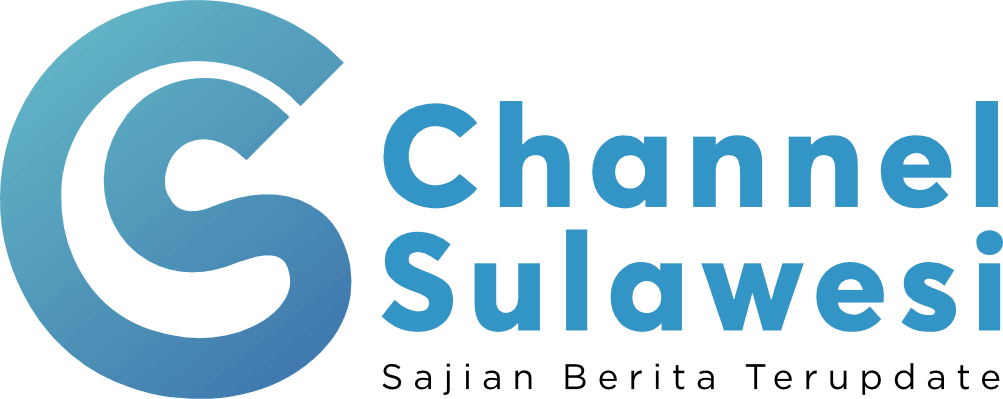Biasanya, kejahatan lingkungan berisik. Ada teriakan warga, spanduk protes, atau setidaknya perdebatan panjang di ruang publik. Namun yang terjadi di Vatutela, Kelurahan Tondo, justru sebaliknya.
Sunyi, terlalu sunyi untuk ukuran sebuah kawasan yang bukit-bukitnya dikupas, tanahnya dibongkar, dan vegetasinya dihilangkan nyaris sampai ke akar.
Selama ini perhatian publik tersedot ke Poboya, lokasi yang sudah telanjur menjadi simbol tambang emas ilegal di Kota Palu. Fokus itu membuat wilayah lain seperti Vatutela luput dari sorotan. Padahal, citra satelit dan temuan lapangan menunjukkan luka ekologis yang tak kalah parah.
Ironisnya, kawasan ini berada dalam peta konsesi PT Citra Palu Minerals (CPM), sebuah fakta yang semestinya memicu kewaspadaan berlapis, bukan pembiaran berlapis.
Pertanyaannya bukan lagi apakah kerusakan terjadi, melainkan mengapa ia berlangsung begitu senyap.
Keheningan jarang lahir secara cuma-cuma. Di Vatutela, ia tampaknya dibayar cukup mahal. Skema sewa lahan dengan nilai hingga Rp30 juta per kapling per bulan menjadi semacam peredam suara sosial. Angka yang bagi banyak warga terasa seperti jalan keluar cepat di tengah ekonomi yang serba sulit.
Sebagian tokoh masyarakat dan pemuda disebut ikut “diberdayakan”. Kata ini biasanya identik dengan penguatan kapasitas, kemandirian, dan keberlanjutan. Namun dalam konteks ini, pemberdayaan terasa lebih mirip kompensasi moral, cukup untuk membuat tenang, tapi tak pernah cukup untuk membuat berani bersuara.
Di sinilah persoalan etika mulai longsor. Tokoh sosial, yang dalam banyak masyarakat lokal berfungsi sebagai kompas nilai dan penjaga kepentingan bersama, perlahan bergeser menjadi penerima manfaat individual. Bukan karena mereka jahat, melainkan karena sistem yang bekerja memberi insentif pada diam, bukan pada sikap kritis.
Secara geografis, Vatutela bukan wilayah sembarangan. Ia berada di kawasan hulu. Dalam logika ekologi, hulu adalah ruang kendali. Apa yang terjadi di sana akan menentukan nasib wilayah di bawahnya (Tondo Duyu-Tondo Ngapa).
Ketika bukit dikupas dan tanah dibiarkan terbuka, kemampuan alam menyerap air hujan menurun drastis. Air tak lagi meresap perlahan, melainkan meluncur cepat membawa sedimen ke sungai. Dalam teori pengelolaan daerah aliran sungai (watershed management), kondisi ini adalah resep klasik menuju banjir bandang.
Artinya, warga di wilayah hilir seperti Tondo Duyu, dan Ngapa sedang hidup dalam semacam undian bencana. Mereka mungkin tak menikmati sewa lahan atau limpahan ekonomi sesaat, tetapi hampir pasti akan menerima dampak ekologisnya. Alam, dalam hal ini, bekerja dengan logika yang dingin dan adil, siapa pun yang berada di hilir akan menanggung akibatnya.
Ancaman yang Tak Terlihat Mata
Jika kerusakan fisik masih bisa dilihat dari udara, ancaman kimia bekerja lebih halus. Aktivitas pengolahan emas ilegal hampir selalu melibatkan sianida, bahan kimia yang dalam ilmu toksikologi lingkungan dikenal sangat mematikan.
Sianida tidak selalu membunuh secara instan. Ia meresap. Melalui proses leaching, zat ini bergerak mengikuti aliran air tanah, mencemari sumur-sumur warga tanpa suara dan tanpa warna. Di Kelurahan Tondo, sekitar 85 persen warga masih menggantungkan hidup pada air tanah untuk kebutuhan sehari-hari.
Paparan jangka panjang, meski dalam dosis rendah, berpotensi menyebabkan gangguan saraf, kerusakan organ vital, hingga kematian. Lebih dari itu, teori bioakumulasi menjelaskan bahwa racun tak berhenti pada satu tubuh. Ia berpindah melalui rantai makanan, menumpuk perlahan, dan sering kali baru “berbicara” setelah bertahun-tahun. Korbannya bukan hanya generasi hari ini, tetapi mereka yang bahkan belum lahir.
Negara dan Tanggung Jawab yang Menguap
Ketika masyarakat sipil memilih diam, entah karena lelah, takut, atau terikat kepentingan. Maka tanggung jawab negara seharusnya hadir lebih keras. Namun yang tampak justru sebaliknya, pembiaran yang nyaris sistemik. Bahkan secara terbuka salah satu petinggi institusi penegak hukum di daerah ini sangat tegas menampik keberadaan aktivitas tambang ilegal itu.
Tambang ilegal bukan sekadar pelanggaran administratif. Ia adalah kejahatan ekologis dengan dampak lintas generasi. Dalam konteks wilayah konsesi, pembiaran juga membuka pertanyaan serius tentang pengawasan, penegakan hukum, dan komitmen pemerintah daerah terhadap keselamatan warganya sendiri.
Bencana tidak pernah bertanya siapa yang menerima uang sewa dan siapa yang menolak. Ia datang tanpa negosiasi.
Uang selalu punya tanggal kedaluwarsa. Ia habis, berpindah tangan, atau kehilangan nilai. Kerusakan lingkungan tidak demikian. Tanah yang rusak butuh puluhan tahun untuk pulih. Air yang tercemar bisa mengubah pola hidup satu generasi penuh.
Vatutela hari ini bukan sekadar lokasi tambang ilegal. Ia adalah cermin tentang bagaimana keheningan bisa dibeli, bagaimana etika bisa dikompromikan, dan bagaimana negara bisa lupa menjalankan fungsinya.
Alam tak pernah lupa. Dan ketika ia mulai menagih, biasanya sudah terlambat untuk sekadar menyesal.
Penulis: Yamin