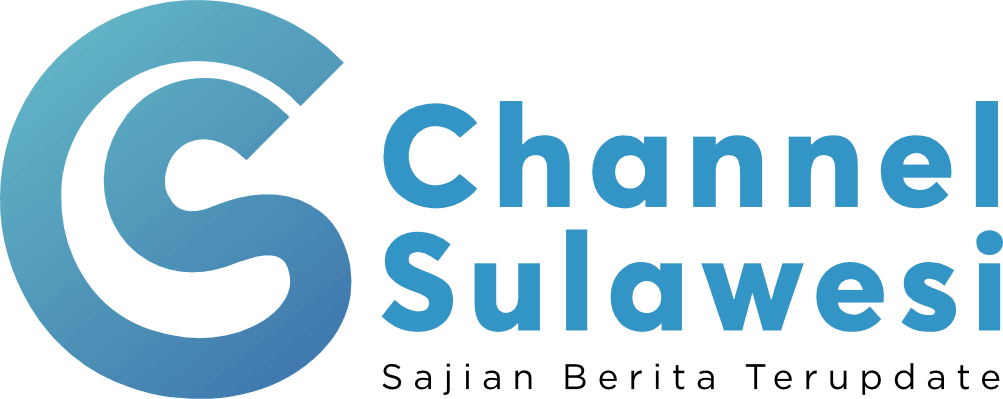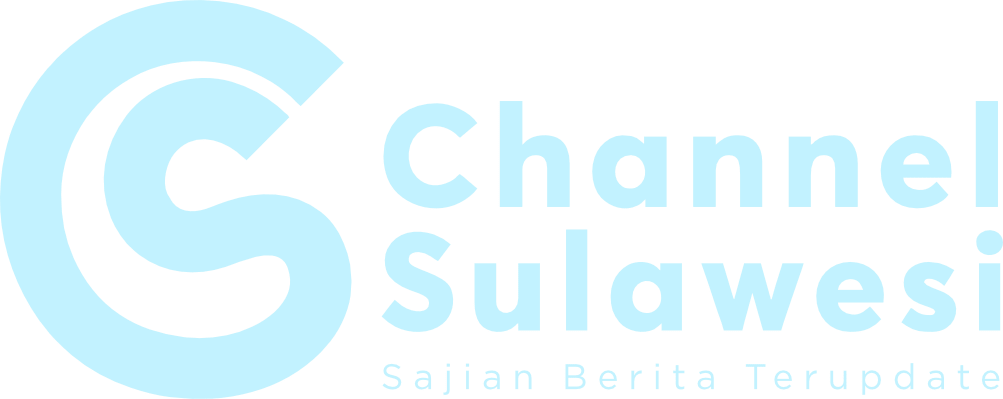JAKARTA, CS – Sejumlah pakar dan pegiat lingkungan menyebut revisi Undang-Undang Kehutanan (UUK) yang saat ini tengah dibahas DPR RI sebagai momentum penting untuk mengakhiri warisan kolonial dalam pengelolaan hutan Indonesia.
Mereka menilai UU Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 sudah tidak lagi relevan dalam menjawab tantangan deforestasi, konflik agraria, hingga krisis ekologis yang terus mengemuka.
Peneliti dari Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Difa Shafira, menyatakan bahwa materi revisi UUK yang digulirkan Badan Keahlian DPR RI dan Panja Komisi IV masih mempertahankan paradigma negara-sentris, tanpa menjawab persoalan substansial.
“Deforestasi seharusnya dapat dicegah dengan memperkuat pemantauan dan penegakan hukum. Fungsi hutan dalam UUK seharusnya diarahkan untuk memulihkan, bukan mengeksploitasi,” tegas Difa Shafira, di Jakarta, Jum’at (11/07/2025).
Ia menambahkan, komitmen Indonesia menekan laju deforestasi melalui Nationally Determined Contribution (NDC) semestinya tercermin dalam revisi regulasi.
Akademisi Fakultas Hukum UGM, Dr. Yance Arizona, menilai UUK masih bertentangan dengan semangat dekolonisasi yang telah diperjuangkan melalui UU Pokok Agraria (UUPA).
“Dekolonisasi hutan berarti memindahkan pusat pengelolaan dari negara ke rakyat sebagai pilar utama. Rule of law kehutanan harus berpijak pada keadilan sosial dan ekologis,” ujarnya.
Menurut Yance, UUK masih menggunakan asas domein verklaring, prinsip hukum kolonial yang mengklaim tanah tak berpemilik sebagai milik negara, padahal UUPA sudah membongkar asas tersebut dan menawarkan pendekatan holistik terhadap tanah, air, ruang angkasa, dan sumber daya alam lainnya.
Senada, Kiagus M. Iqbal dari Sajogyo Institute menyatakan bahwa alam dalam UUPA dipahami sebagai Sumber-Sumber Agraria (SSA) yang menyatu secara sosial, ekologis, dan kultural dengan kehidupan manusia.
“Asas domein verklaring adalah warisan kolonial yang melegalkan perampasan tanah rakyat. Mengapa masih digunakan di era kemerdekaan?” ujarnya.
Sementara itu, Erwin Dwi Kristianto dari HuMa mengkritik konsep Hak Menguasai Negara yang justru memperkuat dominasi negara dan melemahkan posisi masyarakat adat dalam ruang hidupnya.
“UUK seharusnya tidak mengatur penguasaan, tapi perlindungan fungsi ekologis hutan dan pengakuan peran masyarakat adat sebagai penjaga ekosistem,” jelasnya.
Manajer Kebijakan Lingkungan Yayasan Kehati, Mohamad Burhanudin, menyebut revisi UUK seharusnya menjadi jalan menuju keadilan ekologis.
“Pendekatan hukum yang baru harus berbasis ecological law dan mengakui praktik hidup masyarakat adat yang selaras dengan alam. Mereka harus dilibatkan secara aktif dalam pengambilan keputusan,” tegasnya.
Burhanudin juga menyoroti lemahnya akuntabilitas dan transparansi dalam sektor kehutanan.
Ia menilai, tumpang tindih izin, penerbitan izin di kawasan rawan bencana, serta lemahnya pengawasan terhadap korporasi besar memperburuk kondisi hutan Indonesia.
Dr. Martua T. Sirait dari Samdhana Institute menyatakan bahwa proses penetapan kawasan hutan selama ini hanya menekankan aspek teknis administratif dan mengabaikan pendekatan sosial-budaya.
Ia mendorong adanya pendekatan etnografis dan keterbukaan informasi, terutama terkait penetapan batas kawasan hutan.
“Penetapan kawasan hutan seringkali tidak memiliki legitimasi sosial karena masyarakat tidak dilibatkan secara bermakna. Ini tidak memberikan dasar bagi pengelolaan hutan yang adil dan lestari,” katanya.
O.Z.S. Tihurua dari KORA Maluku membagikan pengalaman masyarakat di Maluku yang kaget saat tapal batas kawasan hutan dipasang pada 2020-2022, termasuk di kebun dan rumah mereka, tanpa informasi memadai.
“Selama sosialisasi, masyarakat hanya diberi tahu soal taman nasional, bukan keseluruhan status kawasan hutan,” katanya.
Ia menyebut masyarakat baru menyadari bahwa wilayah adat mereka masuk kawasan hutan negara sejak penunjukan kawasan dilakukan serentak pada 1980-1990-an, dan kini mereka terancam kehilangan tanah yang menjadi sumber penghidupan.
Prof. Agustinus Kastanya dari Universitas Pattimura menambahkan bahwa pendekatan UUK tidak sesuai untuk konteks kepulauan seperti Maluku dan Papua yang memiliki topografi berbeda.
“Pulau kecil harus dikelola dengan sangat hati-hati. Jangan disamakan dengan pulau besar. Apalagi di tengah krisis iklim dan kehilangan biodiversitas,” katanya.
Juru kampanye dari Forest Watch Indonesia, Anggi Putra Prayoga, menegaskan bahwa UUK harus direvisi secara menyeluruh karena secara filosofis, yuridis, dan sosiologis tidak lagi memadai.
Ia meminta DPR dan pemerintah terbuka terhadap kritik terhadap bisnis kawasan hutan yang dinilai tak berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional.
“Sub sektor kehutanan menyumbang paling kecil pada PDB, tetapi kerusakannya berdampak sangat luas. UUK harus diganti total, bukan tambal sulam,” tutup Anggi.**