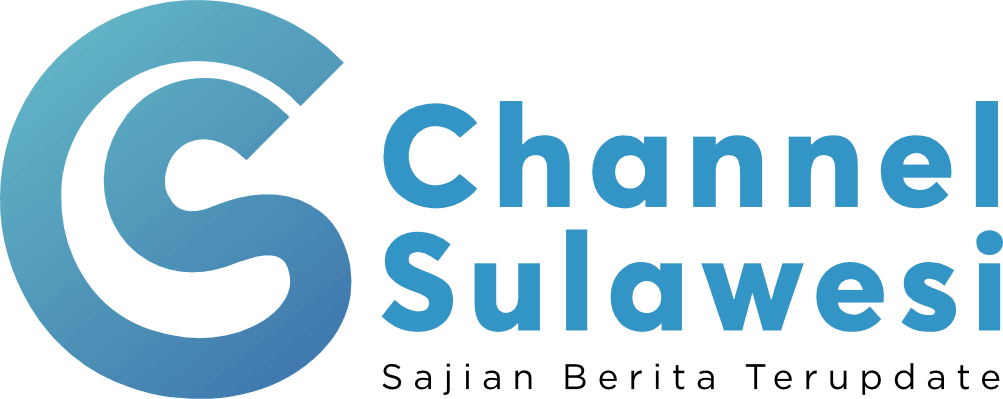Pangan, menjadi isu seksi di era pasca kebenaran. Ia memang tidak setingkat pandemi yang datang tiba-tiba. Tapi wacana krisis pangan seperti “hantu bergentayangan”. Adakah manusia yang bisa melangsungkan hidup tanpa pangan?
Pangan adalah bagian yang inheren dengan tata guna lahan. Dalam pangan, ada struktur, budaya dan kekuasaan yang beroperasi dari waktu ke waktu. Tanah, menjadi kata kunci. Seperti kata para sarjana agraria Indonesia,” siapa menguasai tanah dia menguasai kehidupan,”. Tanah menjadi isu krusial dari waktu ke waktu.
Akar Masalah
Pemenuhan pangan berkaitan dengan akses terhadap tanah. Kelangsungan hidup pemenuhan pangan berkaitan dengan kepastian lahan, kepemilikan dan akses terhadap sarana produksi.
Belum lama ini, isu aglomerasi pangan kembali mengemuka. “Food Estate” menjadi konsep yang dipilih sebagai program ketahanan pangan nasional. Pemerintah menarik asumsi bahwa cara terbaik memastikan pemenuhan pangan adalah kawasan atau aglomerasi.
Pemerintah menetapkan daerah tertentu sebagai kawasan pengembangan pangan. Sebuah daerah di NTT, menjadi pilihan. Pemerintah memastikan daerah tersebut akan diberi sentuhan kebijakan dan menetapkan sebagai titik aglomerasi.
Aglomerasi pangan bukan barang baru bagi kita. Sebelumnya, di Papua juga telah dirintis konsep serupa. Namanya MIFFE, kawasan pangan Merauke yang diinisiasi oleh group bisnis salah satu taipan dari Jakarta.
MIFFE dibangun di atas hutan adat milik suku setempat. Dengan pola bapak angkat, kerjasama pembangunan kawasan itu dimulai dengan land clearing dan pematangan lahan yang menghilangkan hutan Sagu, sumber pangan suku setempat.
Pasca itu, perdebatan mengenai konsep pemenuhan pangan mengemuka, antara kedaulatan pangan dan ketahanan pangan. Pemerintah sejauh ini menghindari konsep kembali ke akar. Tetapi memilih jalan damai, membuka lahan baru.
Antara Land Reform dan Aglomerasi
Masalah agraria di Indonesia dari waktu ke waktu telah dikaji oleh banyak pakar agrari. Letak masalah pangan, erat kaitannya dengan akses, kepemilikan, sarana dan pasar. Ketimpangan atas akses dan penguasaan lahan menjadi topik yang tidak ada habisnya.
Keyakinan kuat menyebutkan bahwa ketimpangan menjadi akar yang mengakibatkan kemampuan pemenuhan pangan di tingkat petani dan masyarakat lokal lemah. Petani dan masyarakat lokal tidak berdaulat atas produksi pangan karena penguasaan lahan dan akses pasar yang lemah.
Land Reform, atau reformasi tanah dan penguatan institusi lokal berbasis inisiatif masyarakat menjadi pilihan. Kata partisipasi adalah kunci dari upaya untuk menciptakan kesanggupan masyarakat dalam pemenuhan pangan.
Tetapi memang, masalah agraria yang kronis dari sejak zaman kolonial ini. Selalu berbenturan dengan tragedi klasik kekuasaan. Inisiatif pembaruan agraria untuk menciptakan kedaulatan pangan bertemu dengan konsep pasar tanah dan kapitalisasi pertanian.
Waktu berlalu, zaman bergerak, akar dari masalah ini tidak kunjung dapat diselesaikan. Malah semakin sengaja dilupakan. Pemilihan konsep food Estate, menunjukan bahwa pemerintah mengambil jalan kapitalisasi pertanian sebagai solusi masalah pangan.
Terlepas dari pemilihan paradigma dan konseptual. Pemenuhan pangan dengan pendekatan kawasan menunjukkan bahwa, partisipasi petani dan masyarakat lokal semakin terpinggirkan. Mode korporasi pangan semacam ini, bisa jadi hanya meniru pola pembangunan Amerika primitif, dan gagal menyentuh akar.
Dengan demikian, hanya ada dua: pemerintah sedang berusaha melupakan apa yang menjadi masalah bangsa; atau sedang ingin membangun ketahanan pangan berbasis monopoli tanah.
Bagi saya, tanpa kedaulatan, ketahanan pangan tidak lebih dari sekedar replikasi konsesi kolonial yang melayani pasar, bukan pemenuhan pangan.*
Penulis : Andika